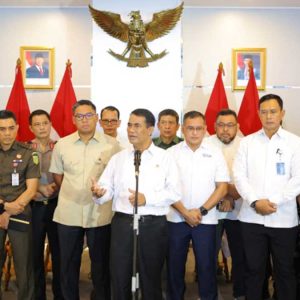InfoSAWIT, BANDUNG – Kelapa sawit sejatinya bukan sekadar tanaman industri—ia adalah makhluk hidup yang bekerja keras, penuh potensi, dan membutuhkan perhatian layaknya manusia. Sawit memang tidak bisa berbicara, tetapi ia “mendengar” perlakuan yang diberikan kepadanya. Ketika dirawat dengan baik, ia membalas dengan hasil yang berlimpah.
Sejak masih berupa kecambah, tanaman ini perlu diasuh seperti bayi manusia. Saat berusia setahun dan ditanam di lapangan, sawit memasuki fase tanaman belum menghasilkan (TBM)—fase yang setara dengan masa balita. Memasuki usia keempat, pohon sawit mulai berproduksi dan terus berbuah hingga umur 25–28 tahun. Dalam periode produktifnya, tanaman ini bisa diajak “berdialog”: apa kebutuhannya, penyakit apa yang diderita, dan bagaimana cara membantunya berbuah lebih banyak.
Secara ekonomis, umur sawit dipatok sekitar 25 tahun. Di usia muda (10–15 tahun), produktivitasnya bisa mencapai 25–30 ton tandan buah segar (TBS) per hektare per tahun. Pada masa dewasa (15–20 tahun), produksinya bisa meningkat hingga 45 ton, dan bahkan di usia tua (20–25 tahun) masih bisa menghasilkan 30–35 ton. Sayangnya, potensi besar ini sering kali tak tergarap optimal karena kurangnya pemahaman pengelola.
Banyak pemilik kebun hanya berfokus mengambil hasil tanpa memperhatikan karakter tanaman. Akibatnya, produktivitas jauh dari potensi ideal—hanya 7–10 ton per hektare per tahun dari potensi 40 ton. Kebun-kebun seperti ini jumlahnya tidak sedikit, diperkirakan mencapai 30% dari total luas lahan sawit nasional, atau sekitar 5 juta hektare, dengan produktivitas minyak sawit hanya 2–2,5 ton per hektare per tahun.
Kebun yang benar-benar terkelola baik juga baru sekitar 30%, dengan produktivitas rata-rata 5 ton per hektare per tahun. Hanya sekitar 5% kebun yang mampu menembus 7 ton minyak sawit per hektare. Sisanya, sekitar 35%, berada di kondisi “abu-abu”—antara dirawat dan tidak. Maka tak mengherankan jika produktivitas nasional baru menyentuh 3 ton minyak sawit per hektare per tahun, jauh dari potensi 11 ton.
Kondisi ini jelas merugikan semua pihak—petani, pengusaha, hingga pemerintah. Pendapatan menurun, pajak berkurang, dan sirkulasi uang di daerah pun menyusut. Pemerintah daerah melalui dinas terkait seharusnya segera memetakan produktivitas kebun: mana yang terawat, mana yang tidak, dan mana yang sangat terawat. Dari peta itu bisa terlihat apakah rendahnya produktivitas disebabkan oleh lemahnya kemampuan teknis dan manajerial, atau karena faktor kesengajaan.
Bagi kebun yang memang kekurangan kemampuan teknis, pembinaan menjadi solusi utama. Alternatif lainnya, lahan tersebut bisa dikelola oleh BUMN perkebunan yang sudah terbukti unggul. Jika 5 juta hektare lahan tidak terawat bisa dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin produktivitas nasional melonjak pesat.
Pemerintah juga perlu segera menyiapkan program pupuk subsidi secara terarah. Perhitungan menunjukkan bahwa subsidi ini bukan beban negara, melainkan investasi produktif. Dengan alokasi Rp 92 triliun pupuk subsidi untuk sawit, potensi penerimaan pajak bisa meningkat menjadi Rp 188 triliun. Artinya, dalam waktu setahun, dana subsidi bisa kembali ke kas negara. Tak hanya itu, akan ada tambahan perputaran uang segar hingga Rp 677 triliun—total Rp 1.230 triliun yang tersebar di 26 provinsi penghasil sawit.